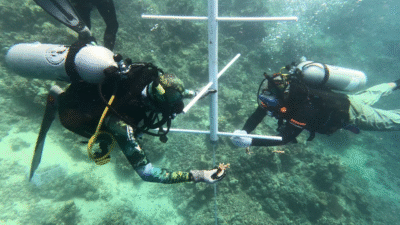Mediatani – Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menuturkan bahwa pemerintah perlu membenahi tata niaga daging sapi nasional yang mana adanya tingginya harga daging sapi baru-baru ini menyebabkan pedagang daging sapi melakukan demonstrasi dan mogok berjualan.
“Fluktuasi harga pangan tentunya ialah hal yang biasa dikarenakan perdagangan pangan itu tidak lepas dari dinamika pasar berdasarkan produksi, distribusi, dan permintaan. Konsumsi daging pun sapi secara umum rendah sekali, hanya sekitar 2 kilogram per kapita per tahun di Indonesia,” kata Felippa lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat (22/1/2021) dilansir dari situs berita Antaranews.com, Minggu (24/1/2021).
Menurutnya, mahalnya harga itu disebabkan oleh harga daging sapi yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp 120.000 per kilogram.
Tingginya harga daging sapi itu kata dia, perlu diatasi dengan melihat ke persoalan di hulu, satu di antaranya ialah karena rantai distribusi yang panjang.
Panjangnya rantai distribusi tersebut menimbulkan biaya tambahan yang tak sedikit. Dan akhirnya berimbas lalu berpengaruh pada harga jual.
Selain itu, pemerintah juga memilih untuk mengimpor sapi bakalan yang harus digemukkan lagi dan dipotong di Indonesia.
Setelah itu, daging sapi yang kemudian dihasilkan dapat dijual langsung ke pedagang grosir berskala besar di pasar atau melalui tengkulak yang membantu Rumah Potong Hewan (RPH) untuk mendapatkan pembeli.
Tahapan berikutnya yakni menjual daging sapi ke pedagang grosir berskala kecil.
Mereka inilah yang menjual daging sapi ke pedagang eceran di pasar tradisional atau supermarket, yang sebelum akhirnya sampai pada tangan konsumen.
Proses panjang ini disebutnya menimbulkan biaya tambahan yang tak sedikit. Saat harga daging sapi naik, maka konsumen akan cenderung membeli komoditas lain sebagai substitusi atau penggantinya. Misalkan, memilih makan ayam atau lauk lainnya.
“Hal ini akan merugikan para pedagang dan tentu bisa dipahami bahwa mengapa mereka enggan menjual daging sapi dengan harga kelewat tinggi. Selain itu, yang paling terdampak dari kenaikan itu juga ialah para pengusaha yang menjual makanan berbahan daging sapi,” terang Felippa.
Dia menyebut para pengusaha makanan siap saji itu dihadapkan pada pilihan, seperti menghilangkan menu daging sapi, mengurangi porsi atau bahkan menambah nilai harga jual.
Di sinilah seharusnya peran pemerintah dapat menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan pada daging sapi.
Perihal wacana impor daging sapi, Felippa mengemukakan pendapatnya bahwa, langkah itu ialah langkah yang strategis untuk dilakukan, juga mempertimbangkan adanya siklus tahunan kenaikan permintaan jelang Ramadan dan pula Hari Raya Idul Fitri.
Produksi daging sapi domestik atau dalam negeri hanya dapat memenuhi sekira 70 persen dari permintaan.
Industri daging domestik pun masih belum mampu bersaing dengan industri daging luar negeri. Sudah tampak berpengaruh bahwa harga tinggi merugikan bukan hanya konsumen tetapi juga pedagang.
“Jadi kami memandang impor sebagai langkah yang tepat untuk mengatasi kesenjangan ini. Namun perlu dicatat, impor juga merupakan kebijakan yang akan efektif jika diikuti adanya data yang akurat dan perkiraan waktu yang tepat dalam mengeksekusinya. Kami juga mendukung impor yang dilakukan secara transparan. Sistem kuota telah terbukti rawan pelanggaran dan hal ini perlu dievaluasi oleh pemerintah,” tegasnya.
Sebelumnya, mahalnya harga daging sapi di Rumah Pemotongan Hewan daerah sekitar Jabodetabek mengakibatkan para pedagang mengeluhkan kenaikan harga daging sapi itu. Hingga akhirnya mereka pun banyak yang memilih berhenti berjualan selama tiga hari, 20-22 Januari 2021. (*)