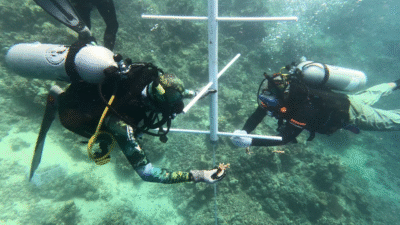Mediatani – Salah satu program utama Presiden Joko Widodo yaitu pembangunan lumbung pangan (Food Estate) di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara menuai banyak reaksi dan protes dari berbagai pihak. Upaya pembuatan food estate tersebut dianggap bukan solusi untuk menghadapi ancaman krisis pangan, apalagi membawa kedaulatan pangan di Indonesia.
Program pembangunan food estate tersebut dinilai tidak belajar dari kegagalan-kegagalan implementasi yang dilaksanakan pemerintah sebelumnya dan tidak berdasarkan kondisi pangan dan pertanian di Indonesia saat ini.
Menurut Serikat Petani Indonesia (SPI), konsep food estate ini akan mengakibatkan produksi pangan di Indonesia akan tergantung dan diurus oleh korporasi pertanian besar baik itu korporasi luar negeri dan Indonesia.
Selain itu, food estate juga akan membutuhkan investasi yang sangat besar yang menghabiskan keuangan negara. Padahal, Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyebutkan bahwa petani dan pertanian kecil yang dikelola keluarga petani (family farming) yang memberi makan masyarakat dunia, bukan korporasi pertanian.
“Food estate tidak bisa jadi solusi atas ancaman krisis pangan yang dikhawatirkan muncul akibat pandemi ini,” ujar Henry Saragih dalam siaran pers, Minggu (25/10).

Di kesempatan yang sama, Ketua Departemen Kajian Strategis Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI, Zainal Arifin Fuad menilai konsep food estate hanyalah menjadikan petani menjadi buruh di negeri sendiri. Ia menekankan, solusinya adalah dengan menerapkan konsep kedaulatan pangan, yang sebenarnya sudah masuk di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
“Petani kecil, keluarga-keluarga petani yang menegakkan kedaulatan pangan di masing-masing daerahnya adalah pahlawan sebenarnya yang harus didukung, bukan korporasi. Terbukti saat krisis 1998, 2008 & pandemi Covid-19. Mereka inilah yang selama ini menopang pemenuhan pangan bangsa, bukan korporasi besar,” tegas Zainal.
Zainal menambahkan, SPI sendiri sudah memiliki konsep kawasan berdaulat pangan yang memberdayakan petani-petani kecil, sudah dipraktekkan dan terbukti menjadi solusi, menjadi harapan untuk menghindari krisis pangan, memberdayakan perdesaan, sekaligus menjadi penopang ekonomi.
“Konsep kawasan berdaulat pangan SPI siap diadaptasi dan menjadi solusi dari food estate yang sudah terbukti selalu gagal. SPI siap bergandeng tangan dengan pemerintah. Kawasan berdaulat pangan juga sudah mengadopsi pasal-pasal dari Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Petani dan Orang Yang Bekerja Pedesaan (UNDROP),” tambahnya.
Kegagalan pembangunan food estate sebelumnya
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudoi, membeberkan rencana pembangunan serupa yang tidak pernah terealisasikan. Dulu, program 1 juta hektare lahan gambut di tahun 1995 dinilai gagal.
Pembuatan lahan ini seluas 1.457.100 hektare dan dibagi lima daerah kerja. Dua tahun anggaran (1996/1997-1997/1998), 31.000 hektare telah dibuka dan ditempati 13.000 KK transmigran, 17.000 hektare sudah dibuka dan belum ditempati, sisa 1.409.150 hektare.
“Food estate Ketapang, tahun 2013 juga gagal. Tercatat ada potensi 886.959 hektare lahan. Tapi Pemda Ketapang hanya berani manargetkan penyediaan 100.000 hektare. Dua tahun berjalan, hanya 104 ha atau 0,1 persen dari target 100.000 hektare yang bisa ditanami dengan hasil beragam yakni 2,77 – 4,69 ton GKP per hektare,” lanjutnya.
Khudori meneruskan, penyebab kegagalan tersebut salah satunya adalah pola kemitraan korporasi-petani selalu diwarnai konflik kuasa atas tanah, tatkala janji bagi hasil tidak sesuai kenyataan. Belum lagi tenaga kerja yang dibawa untuk melakukan program food estate mengalami kerawanan pangan.
“Food estate tahun 2012, di Bulungan juga gagal, dari rencana 298.221 hektare yang direncanakan, luas lahan yang dicetak sesuai laporan pemerintah hanyalah 1.024 hektare dan yang berhasil ditanami hanya 5 hektare,” tegasnya.
Di Merauke, program food estate yang bertajuk Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang menggadang-menggadang akan mengelola 1,23 juta hektare tanah, saat ini hanya bertahan 400 hektare, yang dikelola oleh PT Parama Pangan Papua (anak usaha Medco), bermira dengan petani lokal.
“Penyebabnya adalah transmigran yang menjadi tenaga kerjanya hanya menjadi penopang ekspansi agribisnis, hidup tak membaik, hak tanah tak jelas dan rawan pangan. Selanjutnya, penyamarataan basis pangan beras membuat kualitas hidup warga lokal menurun dan akibatnya jadi rawan pangan juga,” tegas Khudori.
Sementara itu, Muliadi, Direktur Yayasan Petak Danum mengatakan, pasca kegagalan proyek PLG satu juta hektar, sudah ada beberapa kebijakan pemerintah, seperti Kepres Nomor 88/1999 tentang rehabilitasi PLG era Presiden Megawati Soekarno Putri. Juga, Kepres 2/2017 tentang revitalisasi wilayah PLG masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.
“Dari program-program itu, tidak ada keberhasilan nyata. Dianggap gagal jadi lahan pertanian dan lumbung pangan nasional,” katanya.
Masyarakat Kalteng, katanya, mengalami trauma masa lalu dengan kegagalan proyek PLG satu juta hektar itu. Sejak setop 1998, penanganan PLG terabaikan. Bencana terjadi di sana bahkan izin-izin baru terbit untuk perkebunan sawit.
“Ini menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Dampak selanjutnya banjir. Dulu, banjir tidak selama ini. Sekarang, banjir sampai empat bulan. Kemudian, kebakaran dulu tidak besar, sekarang makin luar biasa. Rusaknya ekosistem gambut akibat pembangunan dan kanalisasi di lahan gambut,” katanya dilansir dari Mongabay Kamis (17/9/2020).
Melansir situs Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), pemerintah harus mengeluarkan Rp 3,9 triliun untuk merehabilitasi lahan tersebut. Padahal, proyek PLG telah memakan anggaran Rp 1,6 triliun. Bukan hanya merugikan negara, kegagalan itu juga mengancam biodiversitas tanaman endemik, merusak habitat asli orangutan, dan menyebabkan kekeringan yang menyulut terjadinya kebakaran setiap tahun.